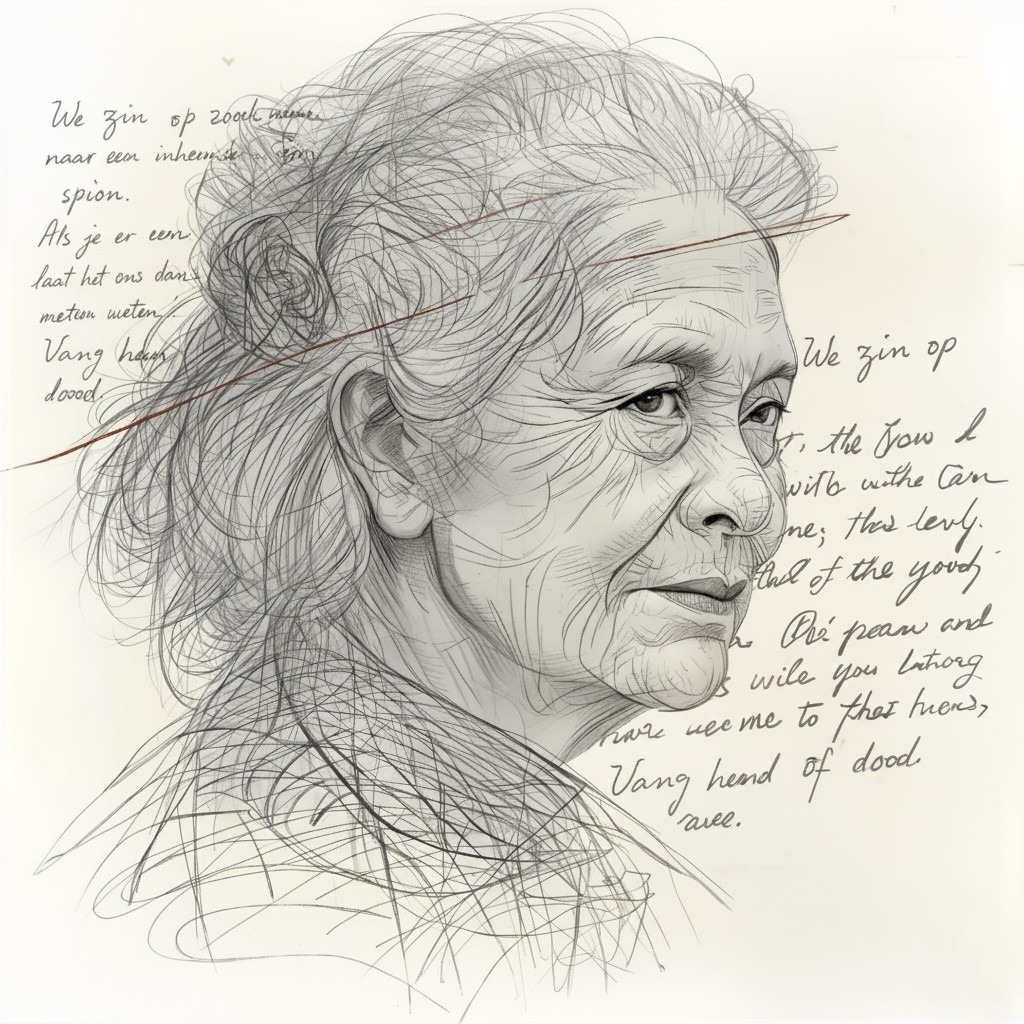
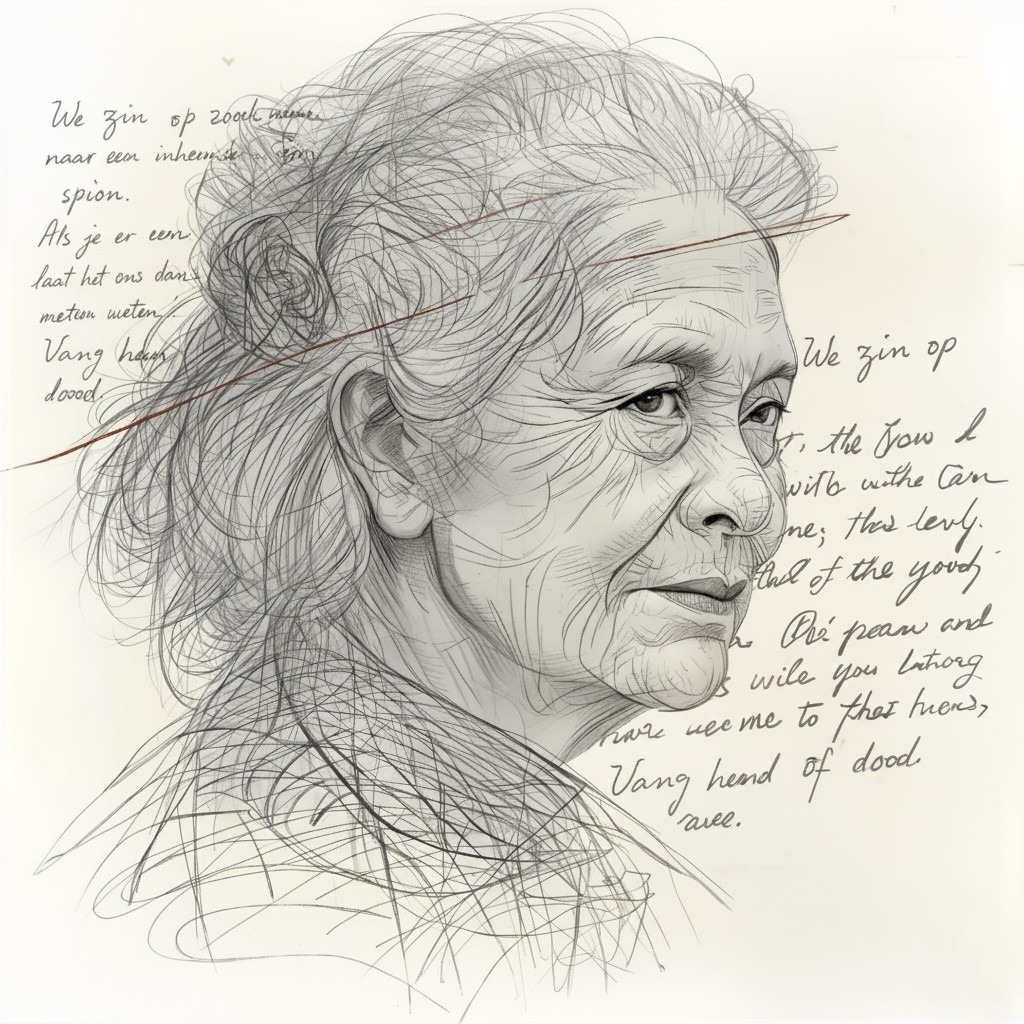
Desa Langgeng yang jauh dari hiruk pikuk kota, hidup seorang wanita tua bernama Dewi Lestari. Rambutnya sudah memutih, jalannya tertatih, namun masih menyimpan cahaya yang sulit dipadamkan. Di tangannya, ada sebuah kotak kayu kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Kotak itu berisi surat yang tidak pernah ia kirimkan.
Setiap pagi, Dewi Lestari duduk di beranda rumah bambunya. Ia membuka kotak kayu itu, mengeluarkan selembar surat dengan kertas yang mulai menguning. Tangannya bergetar ketika menyentuhnya.
Dewi Lestari mulai merintih pelan. “Andai saja dulu aku punya keberanian.”
Surat itu ditulis puluhan tahun lalu, ketika ia masih muda kira-kira tahun 1944. Satu tahun sebelum Indonesia merdeka. Isinya adalah pengakuan cinta untuk seorang pria bernama Prawito, sahabat masa kecilnya. Namun, surat itu tak pernah terkirim. Prawito akhirnya menikah dengan wanita lain, dan Dewi Lestari hanya menyimpan perasaan itu dalam diam.
Suatu siang, di bulan Agustus 2025, seorang pemuda bernama Sastro datang berkunjung. Ia adalah cucu dari tetangga lama Lestari, seorang mahasiswa yang sedang membuat pengganti skripsi tentang pembukuan kisah nyata cinta di desa.
“Nenek Dewi Lestari, aku dengar nenek punya cerita masa muda. Boleh kita berbagi?”
Nenek lestari tersenyum samar, “Cerita masa muda hanyalah bayangan. Apa gunanya untukmu, Nak?”
“Ah, kadang bayangan itulah yang membuat kita mengerti terang, Nek. Maukah nenek ceritakan satu saja?”
Dewi Lestari terdiam lama. Ia menatap kotak kayu di pangkuannya.
“Ada satu surat… surat yang tidak pernah sampai. Mungkin itu bisa jadi cerita untukmu.”
Dengan hati–hati, Dewi Lestari menyerahkan surat itu pada Sastro. Pemuda itu membacanya pelan, matanya membesar saat melihat isi surat yang penuh kejujuran dan kerinduan.
“Nenek… kenapa tidak pernah mengirimnya?”
Dewi Lestari menahan air mata, “Karena aku takut. Takut ditolak, takut kehilangan persahabatan. Jadi aku memilih diam.”
“Dan akhirnya Nenek kehilangan segalanya…”
“Ya, Prawito menikah, punya anak, lalu meninggal beberapa bulan lalu. Aku datang ke pemakamannya, tapi bahkan saat itu aku tak sanggup melepaskan surat ini.”
Sastro menutup surat itu dengan hati–hati. Ia bisa merasakan betapa beratnya penyesalan yang dibawa Dewi Lestari sepanjang hidup.
Malam itu, Sastro kembali ke rumah Dewi Lestari untuk mendengar lebih banyak. Di bawah cahaya lampu minyak, mereka berbincang panjang.
“Nenek, apakah menyesal sekali?”
“Menyesal tentu. Tapi penyesalan bukan berarti aku benci pada pilihanku. Surat ini mengingatkanku bahwa aku pernah berani mencintai, meski tidak berani mengatakannya.”
“Kalau begitu kenapa Nenek masih menyimpannya?”
Dewi Lestari menatap surat, “Karena ia sebagian dari diriku. Tanpanya, aku mungkin lupa pernah punya hati yang bergetar.”
Sastro termenung. Ia membayangkan bagaimana hidup bisa berubah hanya karena satu keberanian kecil atau ketiadaannya.
Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur desa. Sastro berlari ke rumah Dewi Lestari, khawatir wanita tua itu kesulitan. Ia mendapati Dewi Lestari duduk di dekat jendela, menatap derasnya hujan sambil menggenggam surat itu.
“Rintik hujan selalu mengingatkanku pada Prawito. Kami sering berteduh bersama di rumah pohon besar yang tertutup oleh dedaunan. Kami bersembunyi sebagai mata–mata ketika pasukan negeri kincir angin melakukan patroli besar–besaran.”
“Bagaimana jika Nenek menulis surat baru? Bukan untuk mendiang Pak Prawito tetapi untuk diri sendiri. Untuk menutupi luka lama.”
Dewi Lestari menghela napas, “Mungkin kau benar. Tapi aku sudah terlalu tua untuk menutup luka. Aku hanya ingin ada yang tahu, agar ceritaku tidak hilang begitu saja.”
Beberapa hari kemudian, seorang wanita paruh baya datang ke rumah Dewi Lestari. Namanya Sekar Ayu, putri Prawito.
“Nenek Lestari, aku dengar dari Sastro… Anda punya surat untuk ayah saya?”
Dewi Lestari terkejut, menatap sinis Sastro “Kau menceritakan itu?”
“Maaf, Nek. Aku pikir putri mendiang Pak Prawito berhak tahu.”
Sekar Ayu mengambil surat itu dengan tangan bergetar. Ia membacanya, lalu air mata jatuh di pipinya. Surat itu berbunyi;
Oentoek Prawito, sahabat senjapkoe.
Akoe menoelis ini di bawah sinar lampoe minjak jang berkedip, poeloehan tahoen setelah deboe dan mesioe itoe mereda. Tangankoe moengkin keripoet sekarang, tetapi kenangan tentangmoe masih tadjam, sedjelas kode morse jang kaoe ketoek di balik dinding kajoe kita jang rapoeh doeloe.
Kaoe ingat malam-malam tanpa boelan itoe? Kita boekan hanja doea mata-mata jang bertoekar pesan rahasia, boekan? Kita adalah doea bajangan jang saling mendjaga, doea djantoeng jang berdetak seirama ‘aman’ setiap kali kita berhasil melewati patroli besar–besaran. Di tengah-tengah perang jang bising, kehadiranmoe adalah satoe-satoenja kesoenjian jang koeboetoehkan.
Setiap kali akoe memedjamkan mata, akoe masih melihatmoe di roemah pohon persemboenjian, dengan mata jang tadjam mengawasi peta, tetapi matamoe akan melemboet saat melihatkoe. Akoe ingat tjara kaoe membenahi letak selendangkoe sebeloem kita berpisah oentoek mendjalankan misi, seolah sentoehan ketjil itoe adalah djimat jang akan mendjamin kepoelangankoe.
Akoe tak pernah bisa mengatakan ini, karena tjinta di zaman itoe adalah beban jang berat dibawa dalam ransel mata–mata. Djadi akoe mengemasnja rapat–rapat, dibalik senjoem paling biasa dan anggoekan paling profesional saat kita bertemoe.
Tapi, tahoekah kaoe prawito? Setiap sandi jang koeterima darimoe adalah soerat tjinta terindah. Setiap laporan jang kaoe kirimkan, jang memastikan kaoe hidoep adalah satoe tarikan nafas bagikoe.
Akoe tahoe kelak kita menoea, dan kita melandjoetkan hidoep masing – masing seperti jang soedah seharoesnja dilakoekan penjintas. Akoe senang kaoe bahagia. Dan akoe djoega bahagia, tetapi sebagian dari dirikoe selaloe, dan akan selamanja, terkoentji dalam kenangan pada pemoeda jang berani itoe, dimana ketika antjaman terbesar boekanlah peloeroe melainkan kerindoean jang dalam.
Terima kasih karena telah mendjadi alasan bagikoe oentoek selaloe kembali mentjintaimoe.
Tertanda Dewi Lestari.
“Andai ayah tahu ini… mungkin ia akan bahagia. Ayah sering menyebut nama Anda di akhir hidupnya.”
Lestari terdiam, suaranya bergetar, “Benarkah? Ia masih mengingatku?”
“Ya. Ayah saya selalu bilang ada satu sahabat yang tak pernah ia temui lagi, tapi selalu ia doakan.”
Dewi Lestari menangis. Selama puluhan tahun, ia menyimpan perasaan itu sendirian. Ternyata Prawito juga menyimpan kenangan tentangnya. Sekar Ayu menggenggam tangan Dewi Lestari.
“Surat ini tidak pernah sampai pada ayah. Tapi aku dengan senang hati menerimanya sekarang. Biarkan aku menyimpannya sebagai warisan.”
Dewi Lestari masih menangis tersedu “Terima kasih, Nak. Mungkin akhirnya surat ini menemukan tempatnya.”
Untuk pertama kalinya, Lestari merasa beban berat di dadanya berkurang. Ia tak lagi sendiri dalam menyimpan rahasia itu.
Beberapa minggu kemudian, Dewi Lestari duduk di beranda rumahnya tanpa membawa kotak kayu itu. Wajahnya lebih tenang. Sastro duduk di sampingnya.
“Nenek seperti apa rasanya setelah surat itu pergi?”
“Seperti melepaskan burung yang lama terkurung. Ada perih, tapi juga lega. Aku tak perlu lagi menyesal karena akhirnya surat itu dibaca.”
“Dan kisah Nenek akan tetap hidup. Aku akan menerbitkannya dalam cerita pendek.”
Dewi Lestari tersenyum lebar dan tersipu malu “Tulis dengan hati, Nak. Sebab surat yang tak pernah terkirim pun bisa bicara, jika ada yang mau mendengarkannya.”
Hari itu langit senja berwarna jingga. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dewi Lestari memandang ke horizon dengan langkah gontai. Ia tahu hidupnya sudah mendekati akhir, tapi kini hatinya tak lagi kosong.
Surat yang tak pernah sampai akhirnya menemukan jalannya bukan pada orang yang dituju melainkan pada mereka yang masih hidup untuk mengenang. Dan itu sudah cukup.
Penyunting: Arief Kurniawan





























Beri Balasan