

Jangan kaget jika suatu hari ketika kita melangkah ke sebuah minimarket atau hipermarket, rak yang biasanya penuh dengan berbagai merek beras tampak kosong atau hanya menyisakan beberapa karung beras dengan logo Perum Bulog. Fenomena ini sudah terjadi dalam sebulan terakhir, di mana suplai beras medium dan premium kian menipis, bahkan menghilang dari pasar ritel modern.
Bukan hanya perkara distribusi atau pola musiman, melainkan hasil dari sebuah situasi kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, persoalan hukum, dinamika harga di tingkat petani, hingga ketakutan para pengusaha. Lenyapnya beras premium dan medium dari pasar modern adalah gejala dari sebuah sistem pangan nasional yang rapuh, rentan, dan mudah goyah hanya karena satu keputusan atau satu operasi penegakan hukum yang tidak menyentuh akar persoalan.
Pemerintah menyebut pemicu dari masalah ini adalah praktik beras oplosan. Istilah oplosan biasanya memiliki konotasi buruk, padahal di lapangan, praktik mencampur beras dari berbagai kualitas bukanlah hal baru. Banyak penggilingan padi terbiasa melakukannya untuk menghasilkan produk dengan mutu lebih stabil sekaligus memenuhi selera konsumen yang beragam. Ketika praktik ini dipukul rata sebagai pelanggaran hukum, dampaknya seperti bom waktu.
Ratusan pengusaha dijadikan tersangka. Sebagian dari mereka mungkin memang bermain nakal, melabeli beras kualitas rendah seolah-olah premium demi keuntungan besar. Tetapi banyak pula yang sebenarnya hanya melakukan praktik normal dalam industri penggilingan, yakni mencampur varietas atau kualitas beras agar bisa dipasarkan sesuai dengan permintaan pasar. Polisi dan pemerintah, dengan dalih menjaga mutu dan melindungi konsumen, justru membuat pelaku usaha menjadi ketakutan.
Ketakutan inilah yang kemudian menjalar menjadi fenomena penutupan pabrik, penghentian produksi, hingga kekosongan rak beras di pasar modern. Persoalan semakin rumit karena di sisi hulu, petani dan penggilingan berhadapan dengan harga gabah yang melambung. Harga pembelian pemerintah ditetapkan Rp6.500 per kilogram, tetapi realitas di lapangan berbeda jauh. Di banyak daerah sentra produksi, harga gabah sudah tembus Rp7.500 bahkan Rp8.000 per kilogram.
Petani tentu senang karena bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun penggilingan padi dan produsen beras swasta justru terjepit. Jika mereka membeli gabah dengan harga tinggi, maka harga beras yang mereka hasilkan otomatis naik. Masalahnya, pemerintah masih mematok Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Menjual beras di atas HET bisa berisiko dianggap menyalahi aturan, apalagi dengan adanya ancaman proses hukum seperti kasus oplosan tadi.
Di sinilah kebuntuan itu terjadi: ketika produsen beras ingin bertahan, mereka terjebak dalam posisi yang oleh Warkop DKI pernah digambarkan dengan tepat: “maju kena, mundur kena”. Akhirnya, banyak yang memilih tidak lagi memproduksi beras dalam kemasan, bahkan menutup pabrik sama sekali. Dampaknya tidak berhenti di rak minimarket. Di balik pabrik-pabrik beras yang berhenti beroperasi, ada ribuan tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian.
Industri penggilingan padi adalah salah satu penyerap tenaga kerja di pedesaan, menyediakan lapangan kerja tidak hanya bagi buruh penggilingan tetapi juga sopir, buruh angkut, hingga pedagang kecil di sekitar lingkungan pabrik. Ketika pabrik berhenti beroperasi, maka putaran ekonomi lokal ikut terhenti. Situasi ini bisa merembet menjadi persoalan sosial yang lebih besar, terutama ketika masyarakat di daerah penghasil padi juga bergantung pada ekosistem ekonomi yang diciptakan oleh industri penggilingan.
Lebih mengkhawatirkan adalah implikasi jangka panjang bagi konsumen. Jika situasi ini dibiarkan, konsumen hanya akan disuguhi beras SPHP, yakni beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang digelontorkan oleh Bulog. Padahal beras SPHP sebenarnya dirancang untuk konsumen kelas bawah, sebagai bantalan sosial agar harga beras tetap terjangkau. Beras ini bukanlah beras premium atau medium dengan kualitas yang biasa dikonsumsi kelas menengah.
Jika pasar hanya disuplai oleh beras SPHP, maka pilihan konsumen menjadi sempit, selera masyarakat diabaikan, dan kualitas konsumsi pangan kita turun drastis. Negara yang katanya kaya raya sebagai lumbung padi justru hanya bisa menawarkan satu jenis beras kepada rakyatnya, sebuah ironi yang sulit diterima.
Di titik ini, muncul pertanyaan besar: mengapa persoalan pangan di negeri agraris seperti Indonesia begitu rapuh? Jawabannya terletak pada paradigma kebijakan pangan yang cenderung represif, jangka pendek, dan lebih berorientasi pada kontrol daripada pemberdayaan. Pemerintah seringkali memilih pendekatan pemaksaan aturan, seperti penetapan HET dan larangan beras oplosan tanpa memberikan solusi struktural yang membuat rantai pasok beras lebih sehat.
Masalah harga gabah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP). Jika harga pasar sudah bergerak jauh di atas HPP, seharusnya pemerintah meninjau ulang kebijakannya, bukan memaksa penggilingan dan produsen beras menjual murah dengan risiko rugi. Begitu pula dengan persoalan beras oplosan, yang seharusnya dipilah dengan jelas antara praktik curang yang menipu konsumen dan praktik pencampuran yang secara industri memang diperlukan.
Lebih jauh lagi, kebijakan pangan kita masih terlalu bergantung pada Bulog. Lembaga ini memang punya peran penting sebagai penyangga harga dan penyedia cadangan pangan, tetapi ketika Bulog terlalu dominan membeli gabah di lapangan, penggilingan swasta otomatis kehilangan bahan baku. Akhirnya, pasar hanya dikuasai oleh beras Bulog. Ini menciptakan ketergantungan yang berbahaya, karena ketika Bulog tidak mampu menyalurkan beras secara merata, masyarakat yang akan menanggung akibatnya.
Dalam jangka panjang, dominasi satu lembaga negara bisa mematikan dinamika pasar dan merugikan petani maupun konsumen. Di sinilah urgensi pembenahan tata kelola pangan nasional menjadi sangat nyata. Kita butuh kebijakan yang lebih adaptif, yang bisa menjawab dinamika harga di lapangan tanpa mematikan pelaku usaha. Pemerintah semestinya membuka ruang dialog dengan penggilingan padi, produsen beras, asosiasi pengusaha, dan petani untuk merumuskan standar mutu beras yang jelas dan adil, bukan sekadar melabeli semua praktik pencampuran sebagai oplosan.
Jika pemerintah ingin menjaga kualitas, maka harus ada sistem sertifikasi mutu yang transparan, bukan kriminalisasi massal terhadap ratusan pengusaha. Begitu pula dalam soal harga, solusi bukanlah memaksa pengusaha menjual di bawah harga pasar, tetapi menyesuaikan kebijakan harga dengan realitas agar semua pihak tidak dirugikan.
Kebijakan pangan yang baik seharusnya berpijak pada prinsip keberlanjutan. Pangan bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu menjamin ketersediaan dan keberagaman pangan bagi rakyatnya akan selalu berada di ujung tanduk. Apa jadinya jika beras, makanan pokok utama lebih dari 200 juta penduduk, hanya tersedia dalam satu jenis? Apa jadinya jika industri penggilingan padi lokal gulung tikar dan hanya Bulog yang menjadi pemain tunggal?
Ketergantungan semacam ini akan membuat kita rentan terhadap gejolak, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Jangan lupa, Indonesia pernah mengalami krisis pangan pada 1997-1998 yang ikut mempercepat runtuhnya rezim Orde Baru. Pelajaran sejarah seharusnya membuat kita lebih bijak, bahwa soal pangan tidak bisa dikelola dengan cara main pukul rata dan represif. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa pangan adalah bagian dari budaya.
Beras bukan hanya soal karbohidrat, tetapi juga soal selera, kebiasaan, dan identitas masyarakat. Konsumen Indonesia terbiasa memilih beras sesuai dengan tekstur, aroma, dan kualitas tertentu. Menghapus pilihan itu dan menggantinya dengan satu jenis beras SPHP sama saja dengan mengebiri keberagaman budaya konsumsi. Negara seharusnya menghargai keragaman ini dengan memastikan bahwa beras premium, medium, dan berbagai jenis varietas lokal tetap tersedia di pasar.
Itu hanya bisa tercapai jika pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berproduksi tanpa ketakutan, dengan kebijakan harga yang realistis dan regulasi mutu yang jelas. Saat ini kita seolah berada di persimpangan jalan. Jika pemerintah terus membiarkan ketakutan menguasai pelaku usaha, maka industri beras nasional bisa lumpuh.
Tetapi jika pemerintah berani mengambil langkah korektif dengan merevisi aturan, membuka ruang dialog, menyesuaikan kebijakan harga, dan memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, dan petani, maka krisis ini bisa menjadi momentum perbaikan. Jangan sampai kita membiarkan persoalan beras berlarut-larut hingga benar-benar menjadi krisis sosial.
Jangan sampai kita hanya menyadari betapa pentingnya industri beras ketika sudah terlambat, ketika nasi sudah menjadi bubur. Beras bukan sekadar komoditas. Ia adalah simbol dari kedaulatan pangan dan ketahanan bangsa. Jika kita gagal mengelola beras, maka kita gagal menjaga salah satu fondasi utama kehidupan masyarakat.
Saat ini, yang dibutuhkan bukanlah tindakan represif, melainkan kebijakan yang berpihak pada keseimbangan: melindungi konsumen tanpa mematikan produsen, menjaga kualitas tanpa mengekang inovasi, dan menstabilkan harga tanpa mengorbankan petani maupun industri. Hanya dengan cara itu kita bisa keluar dari jebakan “maju kena, mundur kena” yang menjerat pelaku usaha beras, dan hanya dengan cara itu pula rak-rak di minimarket akan kembali penuh dengan berbagai pilihan beras yang layak dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat.
Penyunting: Aprilla Ragil Argiyani
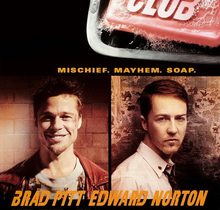












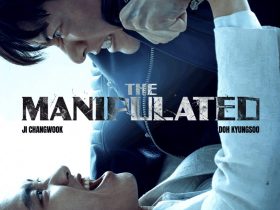




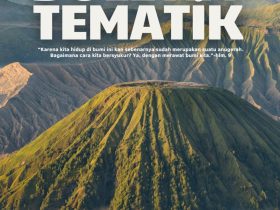










Beri Balasan