Manusia, Alam, dan Paradigma
Sumber: deviantart.com
Oleh:
Achmad Hanif Naufal
Perkembangan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan hidup. Pada satu
sisi, banyak yang terbantu dengan mendukung adanya kemajuan ini. Akan tetapi,
di sisi lain, tidak menutup kemungkinan, hal tersebut sejatinya malah memberikan
keprihatinan bagi stabilitas alam. Pencemaran ekosistem, perampasan keanekaragaman hayati, hingga isu pemanasan
global menjadi permasalahan yang serius. Tercatat sebanyak 318 daerah aliran
sungai (DAS) seluas 3 juta Hektare berada dalam konsidi yang sangat buruk. Laju
kerusakan hutan meningkat hingga 1,8 juta hektare per tahunnya, disusul dengan
keragaman spesies yang mulai terancam akibat eksploitasi yang tidak terkontrol.
Tidak hanya itu, pengerukan bumi untuk industri pertambangan makin liar,
mendegradasi vegetasi dan menyebabkan berubahnya komposisi tanah akibat limbah
pertambangan (Sutoyo, 2013). Rusaknya tatanan kehidupan seperti ini akan mengancam peradaban dan hanya dapat disadari
oleh mereka yang memiliki penyadaran diri, yakni manusia.
Berbagai ilmuwan modern
memandang masalah lingkungan sebagai kasus objektif, sehingga tak ada hentinya
mereka mengembangkan teknologi mengikuti urgensi permasalahan yang ada.
Pasalnya, pendewasaan teknologi tanpa kritik ekosofis justru mereduksi
kemampuan refleksi historis manusia atas persepsinya terhadap alam. Pernyataan
ini dibenarkan oleh Saras Dewi dan Robertus Robert dalam seminar telaah
disertasi filsafatnya yang bertema Manusia dan Lingkungan (Abdalla,
2013). Ketergantungan manusia terhadap alam tidak terlepas atas dasar bahwa
manusia merupakan makhluk egosentris sekaligus ekosentris (Sugiharto & W.,
2000), sehingga fenomena tersebut melampaui fakta bahwa usaha romantisisme
manusia dalam memahami lingkungan secara ontologis masih berlangsung hingga
saat ini (Keraf, 2014). Fritjof Capra (2001) menegaskan perlunya pemahaman
kehidupan atas ekologi holistik, yang berusaha menempatkan manusia dalam
tatanan ekosistem. Pemahaman seperti ini dapat diharapkan melalui peran
pendidikan dalam membangun konstruksi pemikiran yang utuh dan kritis.
Sonny A. Keraf (2014)
merentangkan tingkat pandangan eksistensi ekologi dan manusia pada tiga
paradigma teori etika lingkungan, yakni etika lingkungan dangkal (shallow
environmental ethics) atau antroposentrisme, etika lingkungan medium (intermediate
environmental ethics) atau biosentrisme, dan etika lingkungan dalam (deep
environmental ethics) atau ekosentrisme. Antroposentrisme berkaitan dengan
penempatan posisi moral, instrumentalisasi alam, dan hak aristokrat biologis
atas manusia. Tingkat tengah ada biosentrisme yang merupakan penyeimbang antara
komponen-komponen alam yang saling memiliki ketergantungan dan relasi, sehingga
segalanya patut dihargai. Tingkat tertinggi ada Ekosentrisme yang merupakan
pemusatan alam dan seluruh komponen alam baik biotik maupun abiotik sebagai
sumber nilai dan acuan moral tanpa terkecuali.
Di antara ketiga
paradigma ini, hidup manusia-manusia yang masih memperjuangkan moral maupun
aristokrasi saja. Seakan gaungan
mahasiswa tidak pernah terbayarkan hingga akhir. Pada akhirnya, ego manusia
bersembunyi dibalik realistisme dan empirisme.
DAFTAR PUSTAKA
Abdalla, U. A., 2013. Saras Dewi; Robertus Robert;. Jakarta:
Associate freedom Institute.
Capra, F., 2001. Jaring-Jaring
Kehidupan : Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan. Fajar Pustaka Baru.
Yogyakarta.
Keraf, A. S., 2014. Filsafat
Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan. PT Kanisius.
Yogyakarta
Sugiharto, I. B. & Rachmat, A.,
2000. Wajah Baru Etika & Agama. Yogyakarta: Kanisius.
Sutoyo, 2013. Paradigma Perlindungan
Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum, 4(1): 192-206.
Editor : Dewi Sulastri













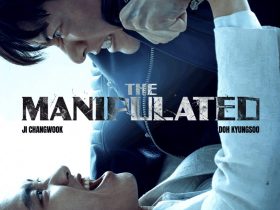





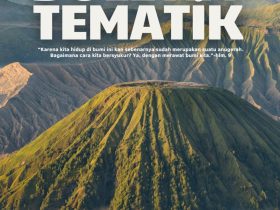










terimakasih kak,sangat informatif dan keren sekali tulisannya
kereeeennnnnnn