

Pernahkah kamu terpikirkan mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Padahal, masih banyak sumber karbohidrat lain yang melimpah di Indonesia dengan gizi yang setara, seperti jagung, kentang, singkong, ubi jalar, talas, dan masih banyak lagi. Hanya sebagian kecil masyarakat di Indonesia bagian timur yang mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok mereka.
Menurut data dari Alodokter, dalam 100 gram porsi yang sama, singkong memiliki kandungan karbohidrat yang lebih banyak daripada nasi, yakni hampir 40 gram. Di sisi lain, ubi jalar memiliki karbohidrat lebih sedikit, namun kaya akan vitamin A dan serat yang jauh lebih tinggi. Singkong, jagung, dan talas juga mengandung nutrisi dan serat yang tidak kalah dari nasi.
Tidak hanya kaya akan varietas karbohidrat, Indonesia juga diberkahi dengan kondisi tanah yang cocok untuk menanam semua sumber karbohidrat itu. Mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah, tanah kita bisa ditanami jagung, singkong, ubi, atau talas dengan subur. Keberagaman geografis dan iklim ini seharusnya menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat dan beragam. Namun, potensi ini seolah sengaja diabaikan, digantikan oleh obsesi tunggal pada nasi.
Jika karena alasan iklim Indonesia cocok untuk menanam padi, mengapa hingga sekarang Indonesia masih mengimpor beras? Jelas, Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan beras seluruh rakyatnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Fakta bahwa tanah Indonesia cocok untuk berbagai tanaman adalah kunci untuk menunjukkan bahwa ketergantungan pada nasi bukanlah takdir geografis, melainkan faktor lain.
Jika dilihat dari sejarah, jauh sebelum Indonesia modern, masyarakat Nusantara sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan dari beragam sumber lokal. Para pakar, seperti yang disebutkan oleh Cakranegara, menyebutkan bahwa padi dibawa oleh pedagang dari Tiongkok dan India. Sebelumnya, sagu adalah pangan pokok utama di banyak wilayah, dan bahkan kata sega dalam bahasa Jawa yang kini berarti “nasi” merupakan istilah turunan dari sagu.
Dari Idealisme Soekarno ke Politik Beras Orde Baru
Idealisme Presiden Soekarno lah yang pertama kali mengangkat isu diversitas pangan dan kedaulatan pangan, memimpikan Indonesia yang berdikari dan berdaulat. Ia secara pribadi mengampanyekan konsumsi makanan pokok selain nasi dan bahkan menginisiasi buku masakan legendaris Mustika Rasa untuk mengembalikan keberagaman pangan. Namun, upaya idealis ini tidak terwujud secara masif. Perhatian pemerintah saat itu lebih terfokus pada masalah politik seperti pembebasan Irian Barat, yang menyebabkan anggaran untuk program diversifikasi pangan sangat minim. Kondisi ini membuat Soekarno akhirnya menggeser fokusnya ke kebijakan jangka pendek yang berpangkal pada persediaan beras yang cukup, yang justru membuka jalan bagi obsesi di era selanjutnya (Cakranegara, 2022).
Pada era Presiden Soeharto, obsesi pada nasi kemudian didorong dan dimaksimalkan melalui program Revolusi Hijau yang tertuang dalam kebijakan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Kecenderungan kebijakan pangan yang dijalankan di era Soeharto yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade adalah mengulang sejarah kolonial, yakni hegemoni pemerintah atas pemenuhan pangan dalam bentuk keseragaman, bukan keberagaman. Nasi dijadikan alat politik Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas politik (Cakranegara, 2022). Bustanil Arifin, Kepala BULOG (Badan Urusan Logistik) saat itu, mengakui bahwa timbul tenggelamnya gerakan penganekaragaman pangan selalu terjadi seiring permasalahan dalam peningkatan produksi beras, karena fokus utama pemerintah saat itu adalah mencapai swasembada beras.
Melalui program-program seperti Bimbingan Massal (Bimas) yang tercantum dalam Repelita, pemerintah secara sistematis mendorong petani untuk menanam padi. Mereka menyediakan bibit unggul, pupuk, pestisida, dan sistem irigasi, yang membuat pertanian lokal yang beragam berubah menjadi pertanian komersial yang seragam dan hanya berfokus pada padi. Jargon “Revolusi Hijau” ini secara perlahan menggusur diversitas pangan pokok lokal. Bibit lokal yang sudah dimiliki petani diganti dengan bibit transnasional yang dikuasai oleh tangan korporasi. Selain itu, Revolusi Hijau juga mengulang kembali kebijakan pemerintah kolonial yang hendak mempertahankan harga beras serendah mungkin untuk menunjang upah buruh industri yang murah sehingga sektor pertanian dijadikan pendukung sektor industri, bukan sebaliknya (Cakranegara, 2022).
Kebijakan ini juga secara fundamental mengubah cara pandang masyarakat. Beras menjadi simbol status sosial. Mereka yang tidak makan beras digolongkan orang miskin. Peningkatan konsumsi beras dan bergesernya pangan pokok lain, seperti jagung atau sagu, disebabkan pandangan masyarakat bahwa kedudukan beras relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pangan pokok lain (Arifin, 1994 dalam Cakranegara, 2022). Pemerintah bahkan menjadikan beras sebagai komponen gaji bagi para pegawai negeri sipil dan tentara di seluruh Indonesia. Secara tidak langsung, mereka menjadi agen penyebar budaya nasi ke seluruh pelosok negeri, menggusur kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak lama.
Meskipun Revolusi Hijau berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984, keberhasilan itu hanya membawa keberhasilan semu. Jurnal-jurnal mencatat bahwa impor beras tetap deras pascaswasembada tercapai. Revolusi Hijau yang menekankan pupuk, benih unggul, dan distribusi tunggal oleh BULOG ini akhirnya mewariskan masalah sosial, pertanian, dan ekologi. Bahkan, hal yang lebih parah terjadi, yaitu pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan industri. Hal ini membuktikan bahwa program pembangunan yang koersif dan berorientasi komersial tersebut telah merusak warisan diversitas pangan Nusantara.
Warisan Ketergantungan
Sayangnya, obsesi terhadap beras ini tidak diatasi oleh presiden-presiden selanjutnya. Ketergantungan ini justru menjadi warisan yang terus berlanjut hingga era Reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, gerakan ketahanan pangan tidak berjalan maksimal. Kebijakan seperti pembagian beras miskin (raskin) bahkan justru semakin menguatkan beras sebagai alat politik dan standar hidup seragam, bahkan hingga ke pelosok-pelosok daerah yang masyarakatnya secara tradisional bukan pemakan nasi.
Hal serupa terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun dilanda krisis gizi buruk yang dialami ribuan anak, kebijakan pertanian masih berfokus pada beras. Alih-alih menguatkan diversitas pangan lokal, kebijakan liberalisasi perdagangan dan proyek-proyek besar seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) justru menyebabkan alih fungsi lahan pertanian secara masif. Ini membuat komoditas pangan lokal kalah bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi petani dan keragaman pangan.
Bahkan pada masa Presiden Joko Widodo, visi ketahanan pangan masih berfokus pada swasembada beras yang diwujudkan melalui kebijakan cetak sawah baru atau program lumbung pangan (food estate). Meskipun proyek ini mencakup komoditas lain, fokus pada proyek skala besar ini dinilai mengancam diversitas pangan pokok yang telah ada dan berpotensi mengulang kesalahan masa lalu. Strategi terpusat semacam ini berpotensi merusak ekologi dan sistem pangan lokal demi mengejar target produksi yang seragam.
Melihat ke depan, tantangan yang sama akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam berbagai janji kampanye, ia menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi kekuatan nasional, dan ambisi untuk mencapai swasembada pangan untuk beragam komoditas telah dicanangkan. Namun, semangat ini dihadapkan pada kritik yang sama: meskipun pemerintahan Prabowo gencar mengatasi masalah pupuk subsidi dan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang menguntungkan petani, fokus utama kebijakan masih condong pada proyek pangan skala masif. Kebijakan ini, yang diperkuat oleh capaian rekor stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog yang menembus 4 juta ton, kembali memprioritaskan beras di atas segalanya. Intinya, tantangan terbesar bagi pemerintahan ini adalah membuktikan apakah mereka akan melanjutkan obsesi pada solusi skala besar yang terbukti berisiko, atau benar-benar berinvestasi pada diversifikasi berbasis kearifan lokal untuk membangun ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kembali ke Jati Diri Bangsa
Saatnya pemerintah kembali ke jati diri Indonesia, di mana keragaman pangan adalah kearifan lokal yang telah ada sejak lama. Kita harus mengikis habis stereotip “belum kenyang kalau belum makan nasi” yang merupakan warisan sejarah yang tidak relevan. Indonesia bisa melepaskan diri dari ketergantungan tunggal pada beras dengan menggali kembali kekayaan alam yang melimpah dan beragam. Kembali ke keragaman pangan bukan hanya soal selera, melainkan fondasi penting untuk membangun ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan.
Daftar Pustaka
Alodokter. (2022, 10 Oktober). 8 Pilihan Karbohidrat Pengganti Nasi yang Mudah Ditemukan dan Bernutrisi. Diakses dari https://www.alodokter.com/8-pilihan-karbohidrat-pengganti-nasi-yang-mudah-ditemukan-dan-bernutrisi
Cakranegara, J. J. S. (2022). Diversitas Pangan Pokok dalam Sejarah Kebijakan Pangan di Indonesia. Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya, 6(1), 17–40.
Indonesia.go.id. (2025, 2 Juni). Swasembada Bukan Lagi Wacana, Program Pertanian Prabowo Sentuh Petani. Diakses dari https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9451/swasembada-bukan-lagi-wacana-program-pertanian-prabowo-sentuh-petani?lang=1
Penyunting: Arief Kurniawan
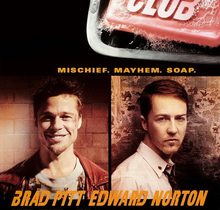












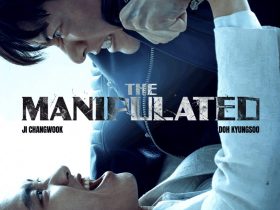




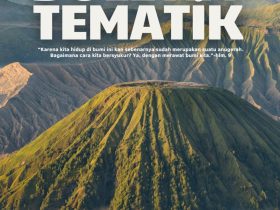








Beri Balasan